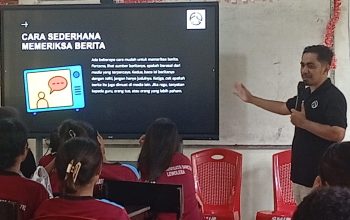RD Patris Allegro*
“Mengapa NTT Terus Dimiskinkan? Tentang Rasa Rendah Diri, Kuasa, dan Mesin Oligarki.”
Di negeri ini, kemiskinan sering dibicarakan seperti cuaca.
Datang dan pergi.
Seolah tak ada yang bisa dilakukan. Seolah ia nasib.
Di Nusa Tenggara Timur, kemiskinan bahkan sudah seperti identitas.
Ia dilekatkan.
Diulang.
Diajarkan sejak kecil.
“Daerah tertinggal.”
“Wilayah pinggiran.”
“Perlu perhatian khusus.”
Kalimat-kalimat ini terdengar simpatik. Padahal di baliknya tersembunyi logika kuasa:
“Engkau miskin, maka engkau pantas diatur.”
Dan dari sinilah cerita panjang dimulai.
NTT tidak miskin karena malas.
Ia miskin karena terlalu lama ditempatkan dalam posisi bergantung.
Ketergantungan adalah bentuk kekuasaan paling halus.
Tidak memukul.
Tidak mengancam.
Cukup membuat orang selalu kekurangan.
Orang yang kekurangan, tidak sempat berpikir jauh. Tidak punya energi untuk bertanya.
Tidak punya waktu untuk curiga.
Yang penting hari ini bisa makan.
Ketika hidup direduksi menjadi urusan bertahan, maka hak politik, kesadaran kritis, dan keberanian moral pelan-pelan mati.
Inilah cara kekuasaan modern bekerja; mengatur manusia lewat kondisi hidupnya.
Lebih dalam dari kemiskinan material, ada kemiskinan yang jauh lebih berbahaya:
rasa rendah diri kolektif.
Selama puluhan tahun, orang NTT dijejali pesan yang sama:
“Kalian tertinggal.”
“Kalian belum siap.”
“Kalian harus dibimbing.”
“Kalian harus berterima kasih.”
Pelan-pelan, pesan itu masuk ke tulang.
Lalu lahirlah generasi yang tidak lagi bertanya:
“Kenapa kami diperlakukan begini?”
Tetapi berkata:
“Memang kami begini.”
Inilah kolonialisme mental.
Penjajahan tanpa tentara. Penaklukan tanpa peluru. Cukup dengan narasi.
Ketika seseorang sudah merasa kecil, ia tidak lagi menuntut keadilan. Ia hanya berharap diberi remah.
Dalam kondisi seperti ini, kapitalisme oligarki masuk tanpa perlawanan berarti.
Dengan bahasa pembangunan.
Dengan jargon investasi.
Dengan janji lapangan kerja.
Tanah diambil. Air dialihkan.
Hutan dibabat. Laut dikapling.
Rakyat diberi kompensasi sekali, perusahaan mendapat keuntungan puluhan tahun.
Ini bukan pembangunan.
Ini penjarahan legal.
Manusia direduksi menjadi tenaga murah.
Alam direduksi menjadi objek eksploitasi.
Dan semuanya dibungkus kata “kemajuan”.
Yang membuat situasi ini langgeng adalah pendidikan yang dipelankan.
Bukan berarti tidak ada sekolah.
Ada.
Bukan berarti tidak ada guru.
Ada.
Tapi pendidikan jarang diarahkan untuk membangunkan kesadaran.
Yang diajarkan: patuh, hafal, lulus.
Yang tidak diajarkan: membaca struktur, mengkritik sistem, melawan ketidakadilan.
Maka lahirlah orang-orang pintar, yang tetap tunduk pada sistem yang merampas hidup mereka.
Budaya pun mengalami nasib serupa.
Kearifan lokal yang dulu mengatur relasi manusia dengan tanah dan leluhur, kini direduksi menjadi tontonan.
Ritual jadi festival.
Makna jadi dekorasi.
Kesakralan jadi konten.
Yang tersisa hanya kulit, sementara jiwanya dicabut.
Masyarakat kehilangan akar. Dan manusia tanpa akar mudah digeser.
Ironisnya, semua ini sering dilegitimasi dengan bahasa agama.
“Sudah kehendak Tuhan.”
“Salib hidup.”
“Nanti dibalas di surga.”
Kalimat-kalimat ini terdengar saleh.
Padahal sering berfungsi sebagai obat bius.
Penderitaan dibuat suci.
Ketidakadilan dibuat normal.
Perlawanan dianggap kurang iman.
Padahal iman sejati selalu berpihak pada martabat manusia, bukan pada sistem yang menghisap.
Jika semua ini dirangkai, gambarnya menjadi jelas.
NTT bukan sekadar miskin.
Ia ditempatkan sebagai wilayah korban.
Penyedia bahan mentah.
Penyerap risiko.
Gudang tenaga murah.
Pasar produk mahal.
Dalam sistem ini, pusat kaya karena pinggiran miskin.
Bukan kecelakaan sejarah.
Ini desain.
Lalu, apa jalan keluarnya?
Bukan baliho baru.
Bukan proyek seremonial.
Bukan bantuan musiman.
Yang dibutuhkan adalah kebangkitan kesadaran.
Kesadaran bahwa,
kita bukan objek. Bukan beban. Bukan penerima belas kasihan. Kita subjek sejarah.
NTT perlu merebut kembali:
Harga diri.
Kedaulatan ekonomi.
Pendidikan kritis.
Politik bermoral.
Iman yang membebaskan.
Budaya yang hidup.
Semua ini tidak datang dari atas.
Tidak dikirim dari pusat.
Ia tumbuh dari bawah, dari komunitas yang berani berpikir, dari intelektual yang tidak mau dibeli, dari rohaniwan yang tidak mau diam, dari rakyat yang tidak lagi takut.
Kemiskinan bukan takdir.
Rendah diri bukan kodrat.
Ketertinggalan bukan kehendak Tuhan.
Semua itu produk sistem.
Dan setiap produk manusia bisa dibongkar, jika manusia berhenti tunduk dan mulai sadar bahwa ia layak hidup bermartabat.
NTT tidak diciptakan untuk menjadi pinggiran selamanya.
Ia hanya terlalu lama dibuat percaya bahwa itulah tempatnya.
Dan kebohongan terbesar dalam sejarah selalu runtuh, ketika orang mulai berpikir.
*Dosen pada Fakultas Filsafat Unika Widya Mandira Kupang